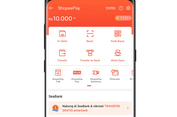Joe Biden dan Ancaman terhadap Transisi Energi Indonesia
Jumlahnya tak main-main, 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 310 triliun. Hal itu seakan memberi angin segar atas pembiayaan transisi energi dalam negeri yang begitu besar.
Rencana gelontoran dana dari negara-negara maju itu disambut hangat Presiden Joko Widodo (jokowi). Namun ada yang perlu digarisbawahi dari rencana Joe Biden dan kawan-kawan tersebut. Model pendanaan itu belum jelas bentuknya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, komitmen pendanaan masih akan dibahas rinciannya. Karena itu merupakan kombinasi dari multilateral development bank, bilateral dan filantropi, maupun hibah. Artinya, ada potensi utang di sini. Ya, pinjaman bermotif utang. Bisa dikatakan, ini ancaman kedaulatan.
Kritik Julius Kambarage Nyerere terhadap Good Governance
Saya jadi teringat kritik terhadap konsep Good Governance (GG) yang disampaikan Julius Kambarage Nyerere, presiden pertama Tanzania. Nyerere mengundurkan diri secara sukarela dari jabatannya karena menyadari kebijakan kepemilikan pertanian komunal dan kepemilikan pelayanan negaranya tak berjalan.
Kritik tersebut, disampaikan di depan Konferensi PBB tentang pemerintahan Afrika tahun 1998. Nyerere memandang GG sebagai konsep imperialistik dan menjajah. Menurut dia, GG akan mengerdilkan struktur negara-negara berkembang. Sementara kekuatan bisnis dunia makin membesar.
Perusahaan-perusahaan donor dan negara-negara maju (seperti AS dan Eropa) menentukan bahwa pemerintahan di Afrika “buruk” dan memutuskan negara-negara itu harus direformasi menjadi “baik” dengan mengecilkan ukuran negara dan administrasi publik, memperluas sektor swasta melalui privatisasi, dan membuka jalan bagi kapitalis global dalam mencari keuntungan tinggi dan terintegrasi ke pasar global.
GG sebagai konsep yang dipaksakan pada negara-negara berkembang dan terbelakang seperti Afrika oleh kekuatan Barat yang terindustrialisasi dan memiliki korporasi global - transnasional. Kata “good”, menjadi sesuatu yang hegemonik dan seragam, yang terkesan dipaksakan.
Ali Farazmand (2004) secara tegas menyebutkan hal itu sebagai bagian dari praktik penyesuaian struktural. Sebab kenyataannya, di berbagai belahan dunia, GG adalah program yang diintrodusir oleh lembaga-lembaga donor internasional, seperti World Bank, IMF, United Nation Development Programme dan European Union atau semacamnya.
Indikator akan sesuatu yang dipakai dalam mengukur berbagai praktik di negara-negara berkembang, baik Asia, Afrika maupun Amerika Selatan/Karibia, tidak ada ruang bagi lokalitas untuk mendefinisikan “good” menurut keyakinan mereka. Apa yang didefinisikan “baik” oleh orang kaya dan kaya secara historis belum tentu baik untuk kaum miskin, kelas bawah, dan massa di negara-negara kurang berkembang.
Tidak ada alasan agar kelompok-kelompok ini memercayai apa yang disebut gagasan baru tentang pemerintahan yang “baik” (Ali Farazmand, 2004).
Dalam konsep itu, negara-negara berkembang dan negara miskin dipaksa menerima konsep dari negara-negara superior dengan kepentingan yang kapitalistik. Pada prinsip ini, standar-standar dalam konsep GG harus dipenuhi negara-negara berkembang dan negara miskin.
Persoalannya, dalam mengejar daulat GG, kekuatan-kekuatan negara maju, berkembang dan miskin, tak sama. Di sinilah superior dan intervensi (kepentingan) negara maju bekerja. Itulah yang melatarbelakangi kritik Nyerere terhadap konsep GG. Ini, gaya penjajahan baru.
Nyerere menyebutnya sebagai konsep yang imperialistik, menjajah. Namun kita tidak bicara mendalam soal kritik terhadap konsep GG yang kemudian melahirkan konsep Sound Governance itu.
Transisi energi bukan hal mudah bagi Indonesia
Kritik terhadap GG di atas merupakan contoh sebuah “konsep” yang menjadi kesepakatan (keharusan) untuk dijalankan, tetapi kemudian berpotensi memoderasi penjajahan gaya baru (neokolonialisme) terhadap negara-negara berkembang maupun miskin.
Prinsip itu, bisa saja terjadi dalam perjanjian-perjanjian internasional yang telah disepakati Indonesia. Salah satunya, transisi energi sebagai salah satu perwujudan komitmen Perjanjian Paris.
Kita tahu, transisi energi dari energi fosil menuju energi terbarukan bukan hal mudah bagi Indonesia. Memang bukan tidak mungkin, bukan tidak bisa, tapi pemerintah kita terlalu candu dan nyaman dengan sumber energi tak terbarukan, seperti migas dan batu bara. Hal itu menjadikan energi fosil seakan mendarah daging bagi masyarakat Indonesia.
Berat bagi negara beralih dan memaksimalkan potensi energi terbarukan. Berat bagi negara ini beralih dari sumber energi migas dan batu bara yang telah menggerakkan perekonomian bangsa berpuluh-puluh tahun.
Perpanjangan kontrak tambang batu bara kepada beberapa perusahaan awal tahun 2022, menjadi sebuah penegasan atas hal itu. Namun seperti yang dikatakan di atas, transisi energi bukanlah tidak mungkin. Meskipun berat dan tertatih.
Semangat transisi energi sebetulnya sudah tercermin dalam dokumen-dokumen perencanaan negara. RPJMN, KEN dan RUEN misalnya. Namun belum menjadi perhatian serius.
Di saat bersamaan, data bauran energi dari Dewan Energi Nasional (DEN) menunjukkan, 91 persen energi primer nasional berasal dari energi fosil (batu bara 37,15 persen, minyak bumi 33,58 persen, dan gas bumi 20,13 persen).
Selaras, tantangan Indonesia yang membuat transisi energi semakin sulit adalah pembiayaan. Selain paradigma/candu energi fosil, pemetaan potensi sumber energi terbarukan, pembiayaan juga menjadi masalah utama, termasuk keberpihakan pemerintah dalam APBN terhadap transisi energi.
Jangan mengorbankan kedalauan negara
Februari lalu, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, transisi energi terbarukan dari energi fosil membutuhkan biaya fantastis. Jumlahnya mencapai 3,5 triliun dolar atau sekitar Rp 50.050 triliun (kurs Rp 14.300) per tahunnya.
Salah satu jawaban atas kebuntuan pembiayaan terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan dalam suatu negara adalah utang luar negeri. Itu jalan pintas. Gampang namun bisa mengorbankan kedaulatan.
Pembiayaan dari utang luar negeri terhadap rencana pembangunan di Indonesia bukan hal tabu. Terkait pembiayaan pembangunan infrastruktur misalnya, dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah 2020-2024 yang dirilis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, pemerintah berencana menarik utang dari pinjaman luar negeri sebesar 25,36 miliar dolar atau setara Rp 360,25 triliun (kurs Rp 14.200 per dolar AS) dalam kurun waktu 2020-2024.
Pinjaman ini akan digunakan untuk membiayai 25 program yang terdiri dari berbagai sektor. Di antaranya, ketahanan sumber daya air, infrastruktur ketahanan bencana, pembangunan jalan tol, transformasi pangan dan nilai tambah pertanian serta pembangunan desa.
Menurut Susan George (1992), utang luar negeri secara pragmatis justru menjadi bumerang bagi negara peminjam (debitur). Perekonomian di negara-negara penerima utang tidak menjadi semakin baik, melainkan bisa menjadi hancur.
Hal itu merupakan salah satu kesimpulan dari hasil penelitian Susan George, yang menunjukkan bahwa pada tahun 1980-an, arus modal yang mengalir dari negara-negara industri maju, yang umumnya merupakan negara kreditur, ke negara-negara yang sedang berkembang dalam bentuk bantuan pembangunan (official development assistance), kredit ekspor, dan arus modal swasta, seperti bantuan bilateral dan multilateral; investasi swasta langsung (PMA); portfolio invesment; pinjaman bank; dan kredit perdagangan (ekspor/impor), lebih kecil daripada arus aliran dana dari negara-negara yang sedang berkembang ke negara-negara maju tersebut dalam bentuk cicilan pokok utang luar negeri dan bunganya, royalti, deviden, dan keuntungan repatriasi dari perusahaan-perusahaan negara maju yang berada di negara-negara yang sedang berkembang.
Kesimpulan Susan George itu, memperkuat argumentasi yang pernah disampaikan GJ Meier (1970), bahwa arus modal asing dari negara maju ke negara dunia ketiga tidak pernah meningkat, dan masalah pelunasan utang luar negeri semakin memberatkan.
Karena itu surplus impor yang ditunjang modal asing semakin merosot, dan pengalihan sumber-sumber di luar impor yang didasarkan pada ekspor menjadi relatif tidak penting bagi sebagian besar negara dunia ketiga.
Selama kendala devisa ini tidak bisa diatasi, negara kurang maju tidak dapat memenuhi kebutuhan impornya bagi program pembangunan.
Akibatnya, negara dunia ketiga itu terpaksa menempuh salah satu atau gabungan dari kebijaksanaan berikut ini: mengurangi laju pembangunan negara, mengembangkan ekspor dan melakukan subtitusi impor untuk memperbaiki term of trade, atau merangsang arus bantuan luar negeri lebih besar lagi.
Ini yang menjadi penekanan saya. Bahwa, transisi energi jangan sampai membawa Indonesia semakin terjerumus jauh ke dalam utang luar negeri. Potensi energi terbarukan Indonesia besar. Begitu juga dengan energi barunya - selain migas dan batu bara.
Jangan sampai pembiayaan untuk transisi energi yang berasal dari utang justru mengorbankan kedaulatan negara terhadap potensi energi terbarukan yang dimiliki.
Letter of Intent (LoI) harusnya sudah cukup menjadi pelajaran, bagaimana pemerintah Indonesia memberikan peluang bagi IMF ikut serta dalam perancangan dan pembuatan banyak keputusan penting di bidang ekonomi, termasuk sektor energi.
Puncak tantangan dari transisi energi Indonesia adalah pembiayaan. Pemerintah perlu merancang skema pembiayaan yang mengedepankan kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat di dalamnya.
Jangan sampai, transisi energi diwujudkan dengan mengorbankan potensi energi terbarukan dikuasai negara asing dan perusahaan multinasionalnya. Bila terpaksa harus menggunakan pembiayaan dari luar negeri (utang) atau ke depannya dalam hal eksplorasi, ekspolitasi hingga pada pemanfaatan energi terbarukan juga tak bisa lepas dari pembiayaan luar negeri - baik dalam hubungan B to G atau G to G, perlu ada rumusan pembagian hasil yang jelas, berdaulat dan adil, bagi Indonesia.
Jangan seperti pembagian hasil eksploitasi emas dengan PT Freeport atau seperti sistem bagi hasil batu bara saat ini, tidak memberikan pembagian yang adil untuk negara. Seyogyanya, skema bagi hasil menempatkan negara sebagai penguasa sesungguhnya, yakni fungsi pengaturan, pengawasan hingga bagian hasil bumi yang lebih banyak.
Idealnya, seperti sistem bagi hasil yang diterapkan dalam eksplorasi dan eksploitasi migas saat ini. Utang luar negeri, jangan sampai mengancam kedaulatan negara atas potensi energi terbarukan di Indonesia.
https://money.kompas.com/read/2022/12/08/095912826/joe-biden-dan-ancaman-terhadap-transisi-energi-indonesia