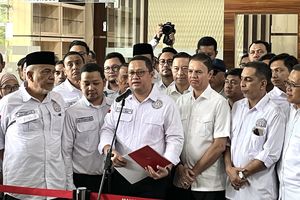Paradok Pajak dan Demokrasi

LAYAKNYA tahun-tahun sebelumnya dengan justifikasi yang tak terlalu jauh berbeda, pandemi Covid-19 juga berhasil membuat rakyat mengizinkan pemerintah untuk merumuskan anggaran jauh di atas kapasitas pendapatan negara.
Rakyat menoleransi defisit dan menerima penambahan utang dengan lapang dada.
Dua tahun lalu misalnya, defisit tercatat Rp 1000 triliun lebih sedikit dan ditutup dengan utang sekitar Rp 600 triliun lebih sedikit.
Sisanya diasumsikan bisa dicari di tengah jalan via efisiensi atau mendorong penambahan pendapatan negara non pajak (PNBP), atau dari pendapatan negara yang sah lainya.
Jika tak tertutup juga, biasanya di penghujung tahun akan dikeluarkan lagi surat utang.
Mengapa rakyat harus mengizinkan? Katakanlah bahwa yang dipercaya untuk memberi ijin adalah wakil rakyat.
Karena pertama, negara kita adalah negara demokrasi. Kedua, karena jika itu ditutup pakai utang, maka akan dibayar cicilannya setiap tahun dari pendapatan negara.
Pendapatan negara dari mana? Pendapatan negara utamanya tentu saja dari pajak yang dibayar rakyat.
Jika tak cukup juga, akan ditambahkan utang baru untuk membayar cicilan atau bunga utang lama. Lagi-lagi agunannya adalah potensi pajak rakyat. Begitulah cara kerjanya.
Lantas apa yang didapat oleh rakyat yang telah membiayai negara atau menjadi tameng utang pemerintah?
Secara politik, rakyat mendapat lembaga perwakilan. Suara rakyat diasumiskan ada di dalam salah satu lembaga pemerintahan. Begitulah memang logikanya.
"Taxation" melahirkan "Representation." Berbeda dengan negara-negara kaya minyak di Arab sana, misalnya. Saat Amerika dan Inggris masuk ke sana, mereka "belaga bego," tutup mata alias menoleransi ketiadaan demokrasi, selama rakyatnya tidak dipajaki.
Formulanya, "No taxation without representation." Dan memang begitu kesepakatanya dengan dunia Arab.
Negara semacam itu mencari pemasukan sendiri, utamanya via pertambangan dan perdagangan minyak, atau via moneteisasi aset monarki.
Sebagian digunakan untuk layanan dasar secara gratis, walaupun layanan sekunder dan tertier biasanya berbayar, tapi cenderung profesional.
Intinya, rakyatnya tidak dibebani pajak, atau tidak terlalu direpotkan dengan pemotongan pajak negara karena tidak diberikan hak representasi.
Di negara-negara tertentu, justru terjadi kombinasi yang unik di mana institusi monarki tetap eksis, tapi institusi representasi juga diadakan, karena diterapkannya fungsi taxasi negara di bidang-bidang tertentu.
Tapi di negara demokrasi, terutama di Amerika, taxpayer atau rakyat adalah penopang nafas pemerintahan.
Pemerintah bisa di-shut down kalau wakil rakyatnya menjegal anggaran yang diajukan pemerintah di satu sisi dan pemerintahnya justru bertahan dengan ajuan anggarannya di sisi lain (deadlock).
Tapi secara prinsipil, demokrasi Amerika sebenarnya juga hanya indah di konsep, karena faktanya rakyat Amerika tak bisa berbuat banyak, kecuali menunggu pemilihan selanjutnya dan vote out atas wakil-wakil yang buruk.
Lumayanlah. Tapi nyatanya setelah pemilihan, wakil rakyat punya kepentingan dan logikanya sendiri.
Dan di Indonesia, dari sisi keuangan (fiskal), negara nampaknya senang bertingkah seperti negara kaya minyak, seolah-olah uang pajak rakyat adalah tambang minyak.
Suara acapkali dibungkam, tapi pajaknya dipunguti secara paksa. Itupun performa pajaknya (tax ratio) masih di bawah standar.
Dan dari segi politik, negara bahkan berpura-pura demokratis, memberi ruang untuk representasi, tapi wakil rakyatnya justru merepresentasikan pemerintah itu sendiri, bukan merepresentasikan rakyatnya. Aneh memang.
Karena itu penguasa dan pemerintah selalu alergi dikritiki, minimal berusaha untuk membuat kritik terdengar sebersahabat mungkin. Kalau sudah tak bersahabat, akan dicarikan cara agar ada pasal yang melibasnya.
Jadi terasa agak aneh karena seolah-olah pemerintahan terpilih (presidency dan legislative) hanya ingin melalui proses demokrasi untuk menapaki kekuasaan saja, selepas itu walahualam.
Selepas itu, justru para elite pemerintahan bak raja Arab, yang menambang uang dari keringat rakyatnya.
Selain tentunya tambang minyak yang asli mereka tambang juga, pakai perusahaan negara atau pakai konsesi-konsesi ke pihak ketiga, berbarengan dengan menambang keringat rakyat.
Dan kalau besok-besok kencing rakyat bisa menghasilkan uang, boleh jadi akan dipajak juga. Kenapa?
Karena ada komplek bangunan segede gaban di Senayan sana, yang diaku sebagai bukti keberhasilan negara menunaikan kewajiban dalam memberikan ruang perwakilan bagi rakyatnya, tak peduli kelakuannya seperti apa.
Toh sudah ada lembaga perwakilan yang gedungnya sangat megah, pesta demokrasinya sangat mahal. Ada representasi, karena itu taxasi mengikutinya.
Anehnya, sebagian pihak di akar rumput tetap memaksakan diri untuk bangga, bahkan ada juga yang terlalu bangga, bertengkar atas nama para pemangaku kuasa, berkelahi seolah-olah kepentingan rakyat ada di dalam daftar prioritas penguasa.
Bahkan saat mereka bertengkar memperebutkan "mesin tambang keringat rakyat" bernama partai politik itu, sebagian rakyat justru bangga saja ikut meramaikannya, ikut berbuih-buih membela salah satunya di berbagai ruang publik.
Jadi seberapa yakin kita bahwa demokrasi yang seharusnya memberi harapan itu, belum dibajak oleh para elite?
Saya sih dari dulu cukup yakin, sudah sedari bayi demokrasi Indonesia dibajak oleh pejabat-pejabat terpilihnya.
Yang terasa hari ini, seolah-olah bagi para elite dan dedengkot ekonomi politik bahwa demorkasi sebenarnya tak ada apa-apanya.
Bagi mereka, demokrasi itu hanya alat untuk memajaki rakyat atas nama negara atau mengatasnamakan rakyat untuk menumpuk utang sekenanya, agar kantong-kantong negara tetap terjamin isinya untuk bisa dibagi-bagi di antara sesama mereka.
Isi kantong negara kemudian dialirkan dari atas ke bawah. Artinya, yang di atas dulu dipenuhi kebutuhannya, lalu mengalir ke lapisan ke dua sampai memenuhi kepentingan dan kebutuhan lapisan kedua, lalu terus ke bawah, begitu seterusnya.
Proyek-proyek dirumuskan utamanya untuk dikerjakan oleh rekan-rekan yang memang sedari awal telah berinvestasi di dalam pesta-pesta demokrasi.
Perkara proyeknya fungsional, mencapai target dan sasaran, atau bersesuaian dengan kepentingan rakyat, itu perkara ke sekian.
Sampai tersisa seadanya untuk lapisan paling bawah, yakni rakyat. Contoh sisa itu, misalnya, seorang anggota DPR menyumbang ini dan itu ke dapilnya.
Yang namanya sumbangan ya barang sisa. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia anggota DPR. Waktu belum jadi anggota DPR, ia biasanya tak begitu.
Padahal bukan itu toh yang diharapkan dari seorang wakil rakyat. Yang diharapkan adalah legislasi yang mewakili kepentingan rakyat (legislating), alokasi anggaran pada kebijakan-kebijakan yang mewakili kepentingan rakyat (budgeting), dan teriakan lantang kepada penguasa yang menyalahi aspirasi rakyat (controlling). Itulah yang seharusnya dilakukan wakil rakyat.
Anggota DPR semacam itu hanya berpikir bagaimana untuk terpilih kembali di laga selanjutnya, baik untuk tetap di posisi semula, atau untuk posisi lain yang lebih prestisius. Segala pemberiannya tentu perlu dihargai.
Setidaknya budaya timur mengajarkan kita begitu. Jika itu mengatasnamakan jabatan wakil rakyat, maka bukan begitu cara kerjanya.
Toh ia tidak dipilih untuk menyumbang, karena menyumbang adalah aksi perorangan.
Tapi nyatanya hanya itu yang mereka berikan untuk demokrasi dan untuk rakyat, karena hanya itu sisa anggaran negara yang Rp 2000 triliun lebih per tahun itu toh, yakni sumbangan.
Itu pun boleh jadi sisa gaji, tunjangan, dan penghasilan negara yang sah lainya yang dibayarkan negara, yang asalnya bisa sebagian dari pajak bisa pula dari utang negara atas nama rakyat.
Atau katakanlah dari sumbangan pihak ketiga (rekanan) yang sebelumnya telah mendapatkan alokasi dana proyek dengan jumlah berkali-kali lipat dari itu.
Jadi, pandemi ini memang memperjelas bagaimana demokrasi berlaku di sini. Ya, di sinilah tersangkutnya demokrasi itu hari ini. Anda memang bisa bilang apa? Memang sudah bayar pajak?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.










![[POPULER MONEY] Mengevaluasi Pajak Kripto | 5 Kesalahan Membeli Emas Batangan](https://asset.kompas.com/crops/MdxGwIpRhzXWRt1aYMI7-19EhFI=/0x1012:2400x2612/170x113/data/photo/2024/04/08/6613a75ae5fa7.jpg)