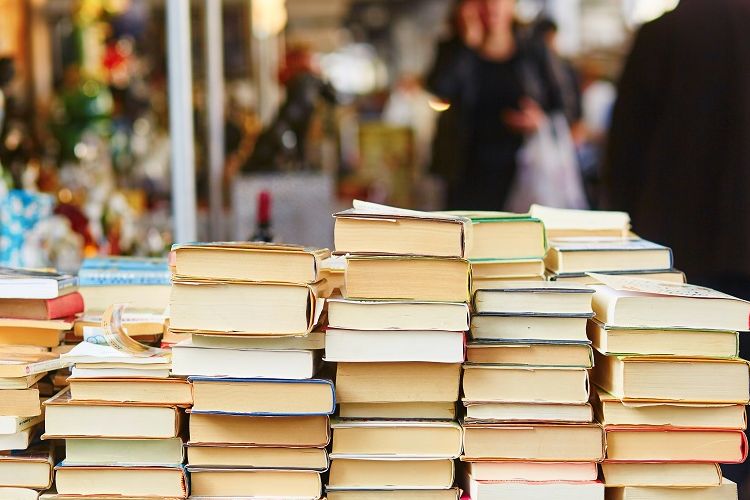Menakar Masa Depan Industri Perbukuan

BEBERAPA waktu lalu, masyarakat Indonesia dihebohkan tutupnya Toko Gunung Agung. Banyak yang menyayangkan tumbangnya jaringan toko buku yang berdiri sejak 1953 tersebut.
Sebelum menutup seluruh jaringan toko bukunya, Toko Gunung Agung bisa dikatakan pernah mengalami masa kejayaannya pada 1990-an. Pada periode tersebut, usaha yang dirintis oleh Tjio Wie Tay tersebut menguasai 25 persen pangsa pasar penjualan buku di Tanah Air.
Tutupnya Toko Gunung Agung secara permanen menjadi kabar buruk bagi kemajuan literasi di Tanah Air. Pasalnya, sebelumnya publik sudah dibuat sedih dengan tutupnya (sebagian) gerai-gerai milik jaringan toko buku kenamaan seperti Books and Beyond, Togamas dan Kinokuniya.
Faktor kehadiran internet
Harus diakui bahwa perkembangan internet menjadi awal anjloknya bisnis toko buku fisik. Pasalnya, kehadiran internet membuat masyarakat bisa lebih mudah membaca buku versi digital (ebook) dengan biaya jauh lebih terjangkau.
Tak mengherankan bila Kindle, Google Play Books atau Gramedia Digital dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren perkembangan yang menakjubkan.
Di sisi lain, budaya membaca buku masyarakat Indonesia memang dapat dikatakan memprihatinkan. Anak-anak muda kita jauh lebih betah berjam-jam menikmati konten digital di YouTube, TikTok, Instagram dan berderet platform media sosial lainnya dibandingkan membaca buku.
Dari perspektif (sebagian) penulis, pendapatan dari menulis buku juga belum dapat diharapkan banyak. Rendahnya besaran royalti, transparansi angka penjualan buku dari (sejumlah) penerbitan yang meragukan, tingginya pajak royalti, dan lesunya penjualan buku menjadi faktornya.
Realita tersebut diperburuk masifnya pembajakan buku yang dijual secara bebas melalui sejumlah ecommerce kenamaan seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan semacamnya.
Tak mengherankan bila profesi penulis kurang menjanjikan di mata generasi "zaman now" dibandingkan menjadi Content Creator, PNS, pengusaha ataupun karyawan di perusahan multinasional.
Faktanya adalah kita perlu menjual banyak buku untuk menjadi seorang penulis yang "sukses". Bagi sebagian besar penerbit tradisional, bisa menjual 2.000 buku dianggap sukses. Angka tersebut adalah rata-rata jumlah eksemplar buku untuk satu periode cetak.
Jika ada kebutuhan yang masih tinggi dari pembaca, maka biasanya penerbit akan mencetak ulang suatu buku.
Namun, berapa banyak uang yang diperoleh seorang penulis dengan menjual 2.000 eksemplar dalam setahun?
Katakanlah harga jual bukunya adalah Rp 50.000 dan royaltinya adalah 10 persen. Maka, dari satu buku yang diterbitkan, penulis akan mendapatkan Rp 10 juta setahun -- itupun jika langsung ludes semuanya.
Bagaimana strategi penulis full time agar bisa bertahan? Tentu saja, dengan menerbitkan semakin banyak buku (best-seller). Tidak sedikit yang menjual keahlian menulisnya menjadi seorang Co-writer, Ghostwriter, Copywriter, hingga Editor.
Faktanya, jumlah penulis full time di Indonesia masih begitu rendah. Sebagian besar menjadikan penulis sebagai "profesi sambilan" dari pekerjaan utamanya.
Kendati harus diakui ada segelintir penulis full time yang bisa eksis atau "sukses". Namun jumlahnya ada berapa? Bisa dihitung dengan jari.
"Lonceng Kematian" industri perbukuan?
Dengan rendahnya minat generasi muda untuk menjadi penulis, makin menurunnya minat masyarakat untuk membaca buku, dan gempuran pembajakan buku; apakah itu semua menjadi pertanda tumbangnya industri perbukuan?
Sebagian analis memang mengatakan bahwa era kejayaan penerbitan tradisional telah berlalu. Sementara itu, sebagian pihak lain mengatakan bahwa industri perbukuan hanya menyesuaikan diri -- bukannya mati -- karena fondasi literasi dan penyebaran pengetahuan masih bergantung pada buku -- bukan pada konten-konten "murahan" berbasis digital.
Penting bagi kita untuk memahami bahwa perdebatan mengenai kelangsungan industri perbukuan masih berkutat pada aspek profitabilitas.
Akankah industri perbukuan terus menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan operasinya pada masa depan, atau apakah industri ini berada di ambang kematian?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor kunci.