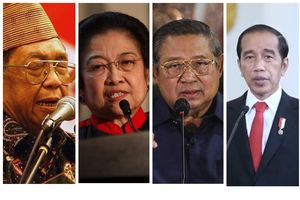"Food Estate" dan "Contract Farming" Jauh dari Kedaulatan Pangan
Mayoritas harga pangan seperti beras, bawang merah, bawang putih, cabai, telur ayam ras, daging ayam ras, hingga daging sapi mengalami kenaikan di tingkat pedagang eceran.
Khusus beras, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga dalam satu tahun terakhir bahkan mencapai 20 persen.
Kenaikan harga beras yang tak terkendali sebagai pangan pokok strategis menunjukan pemerintah tidak sanggup melakukan stabilitas.
Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga rata-rata nasional Beras Medium di Pedagang Eceran pada 28 Februari - 6 Maret 2024 sebesar Rp 14.290/kg.
Angka ini lebih tinggi dari periode sepekan menjelang Ramadhan tanggal 15-22 Maret 2023, yaitu Rp 11.890/kg dan sepekan menjelang Lebaran 15-22 April 2023, yakni Rp 12.120/kg.
Situasi ini menunjukan bahwa harga beras di pasar jauh melampui Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan Peraturan Bapanas 7/2023. HET Beras Medium yang terbagi di setiap zona berkisar antara Rp 10.900 – Rp 11.800/kg.
Persimpangan jalan
Situasi demikian lantas memunculkan pertanyaan: apa solusi yang tepat mengatasi masalah pangan tersebut?
Sesungguhnya UU Pangan dan Pemerintah telah menempatkan kedaulatan pangan sebagai kerangka utama kebijakan. Namun pada pelaksanaan dalam satu dasawarsa ini menjadi bergeser dan bias.
Bak di persimpangan jalan, kedaulatan pangan direduksi ke berbagai wacana teknis seperti pertanian kontrak (contract farming) dan lumbung pangan terpusat (food estate). Bahkan kedua mekanisme ini seolah ditempatkan sebagai solusi baru yang terus ditawarkan.
Secara konseptual, contract farming didefinisikan sebagai upaya ‘integrasi ke dalam satu sistem besar’, di mana terjadi ‘dynamic patnership’ antara petani kecil dan usaha besar, yang memberikan keuntungan bagi keduanya, tanpa mengorbankan pihak lain (Frida Rustiani, dkk., 1997).
Kendati demikian, contract farming bukanlah konsep yang tanpa cela. Contract farming di Indonesia telah dipraktikkan dalam berbagai bentuk, mulai dari Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI), hingga Tambak Inti Rakyat (TIR).
Praktik-praktik contract farming tersebut secara nyata menghadirkan luka bagi para petani, peternak, dan rakyat perdesaan.
Apakah itu dalam bentuk konflik agraria akibat perampasan hak atas tanah, hingga keuntungan yang nyatanya tidak dinikmati penuh oleh para petani. Mengingat adanya relasi kuasa yang timpang dalam praktik contract farming.
Sejak pertama kali diterapkan di Indonesia, contract farming digagas perusahaan perkebunan (plantations estate). Hal ini ditandai dengan UU Penanaman Modal Asing 1967 dan UU Kehutanan 1967, serta peraturan-peraturan lainnya untuk meneruskan keaktifan kembali perusahaan perkebunan asing.
Tak lama setelah itu, Orde Baru atas nama peningkatan pendapatan negara dari sektor non-migas dan pemerataan penduduk menjalankan program transmigrasi dan perluasan perusahaan perkebunan, baik itu perusahaan negara dan perusahaan swasta. Sehingga sejalan antara eksploitasi hutan dan perluasan perkebunan.
Orde Baru berusaha mendapatkan dukungan dari lembaga moneter internasional, misal World Bank.
Contract farming diartikan sebagai suatu cara mengatur produksi pertanian di mana petani-petani kecil atau outgrowers diberi kontrak untuk menyediakan produk-produk pertanian untuk usaha sentral sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian (contract).
Hal ini berangkat dari logika untuk mengurangi keterlibatan langsung dalam produksi primer, dan mendorong praktik borongan atau mengkontrakkan produksi primer kepada petani kecil (Erna Ermawati, 1996).
Contract farming di Perkebunan disebut dengan Nucleus Estate Smallholder (NES). Artinya Perkebunan inti dan rakyat, dan selanjutnya berkembang menjadi PIR Unggas, PIR Udang, dan seterusnya.
Dalam konsep PIR BUN, rakyat menyiapkan tanah, kemudian tanah itu dilegalisasi secara kepemilikan, 30 persen atas nama kepemilikan rakyat, dan 70 persen atas nama perusahaan.
Kemudian pihak perusahaan yang membangun kebun tersebut, dengan melakukan penyiapan lahan (land clearing), benih, pabrik pengolahan, dan peminjaman hutang ke pihak perbankan. Kerja sama ini dituangkan dalam bentuk akte kerja sama.
Begitu juga dengan PIR Unggas, di mana kemitraan antara peternak rakyat dengan korporasi justru mengakibatkan ketergantungan sektor peternakan Indonesia terhadap bibit, pakan, dan kontrol harga.
PIR Tambak juga demikian. Kasus Tambak Dipasena menunjukan kontrak antara petambak dan mitra lagi-lagi tidak menguntungkan.
Analisis yang diberikan para ahli mengapa World Bank menganjurkan sistem contract farming ini ialah tuntutan reforma agraria harus ditanggapi dengan model tersendiri.
Agar reforma agraria yang sudah dijalankan di negara-negara sosialis tidak menjadi acuan tunggal, dan menjadi alternatif reforma agraria yang dijalankan negara-negara barat.
Meskipun kini contract farming telah berkembang dan termodifikasi, namun semangat utama dari mekanisme ini bersandar pada prinsip deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi.
Bagi kapitalis pasar sesungguhnya yang diperlukan bukanlah penguasaan tanah, karena menyangkut pertanahan menjadi tema nasionalisme dan antiimperialisme.
Bagi kapitalis pasar yang dibutuhkan ialah hasil pertanian itu untuk keperluan perdagangan bebas. Karena itu biarlah rakyat tetap punya hak atas tanah, tetapi jenis tanaman dikontrol pasar.
Pengulangan kegagalan
Perdebatan atas solusi pangan juga memunculkan proyek food estate. Pergolakan ini sesungguhnya bukan hal yang baru.
Pada era Presiden Soeharto, proyek serupa dinamakan rice estate. Kemudian dihidupkan kembali oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan kini digaungkan kembali Presiden Joko Widodo di periode kedua.
Food estate kali ini ditandai dengan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang tahunan MPR-RI tanggal 14 Agustus 2020.
Presiden Jokowi mengatakan, dalam menangkal krisis pangan akibat pandemi dan berbagai tantangan global, pemerintah merencanakan food estate atau proyek memproduksi pangan skala luas yang dilakukan oleh negara dengan bantuan korporasi.
Jauh sebelum istilah food estate, sebenarnya ide dasar sudah lama diterapkan pada masa kolonial Belanda dengan nama plantations estate atau perkebunan skala luas.
Plantation estate diintrodusir di Indonesia mengakhiri model pertanian tanam paksa, dan menggantinya sejalan dengan semangat liberalisasi di Eropa dengan membuka ruang bagi perusahaan/korporasi swasta untuk berinvestasi di sektor pertanian/perkebunan.
Untuk mendukung rencana tersebut, maka disahkan UU Agraria 1870 (Agrarische Wet 1870). Sejak itu perusahaan dari eropa ramai-ramai berinvestiasi ke sektor perkebunan untuk ditanami tebu, cengkeh, kopi, karet, dan akhirnya tanaman sawit, sesuai kehendak pasar global sekarang ini.
Oleh karena itu, Pemerintah seharusnya mengkaji lebih dalam penyebab kegagalan proyek-proyek food estate sebelumnya di Ketapang, MIFEE Papua, dan Bulungan. Sebab food estate yang kini digagas tersorot bagai mengulang kegagalan yang sama.
Apalagi secara praktik food estate tidak banyak berubah, sehingga bentuk masalah yang dihadapi masih sama. Mulai dari perumusan kebijakan yang bersifat top-down, problem ketenagakerjaan, mekanisasi pertanian yang tidak tepat, dan pola ‘kemitraan’ korporasi-petani yang tidak ideal.
Kemudian pola jangka waktu yang singkat, sampai jenis tanaman yang belum dikuasai petani, dan ada perbedaan praktik pertanian yang dilakukan masyarakat lokal.
Kedaulatan pangan
Oleh karena itu, contract farming dan food estate sesungguhnya menjauhkan kebijakan pangan di Indonesia dari prinsip-prinsip kedaulatan pangan.
Permasalahan laten pangan semacam produksi, produktivitas, harga, dan impor selalu rutin hadir setiap tahun.
Padahal dibanding korporasi, keluarga petani telah terbukti lebih sanggup memproduksi pangan untuk sebagian besar penduduk dunia, sebagaimana FAO yang mempercayainya dengan menetapkan tahun 2019-2028 sebagai Dekade Pertanian Keluarga.
Secara konseptual, ‘kedaulatan pangan’ merupakan konsep yang menitikberatkan pada hak setiap negara dan rakyat untuk menentukan pangan secara mandiri, meliputi alat dan sistem produksi serta pemasaran di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan untuk menghasilkan pangan tanpa tergantung dari kekuatan pasar internasional.
Berbeda dengan 'ketahanan pangan' yang menjadi paradigma dibalik contract farming dan food estate.
Ketahanan pangan memiliki prinsip: ketersediaan; kecukupan; dan keterjangkauan. Prinsip tersebut merupakan konsepsi liberal yang hendak mengakomodasi kepentingan dari globalisasi ekonomi, setelah WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) terbentuk pada tahun 1995.
Sementara dalam kedaulatan pangan, permasalahan pangan tidak disederhanakan hanya persoalan produksi dan tata kelola niaga semata.
Melainkan juga menitikberatkan hal-hal fundamental lainnya mencakup pengakuan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak asasi petani (tanah, benih, situasi keamanan, kesejahteraan, dan lainnya).
Hal ini dilihat sangat relevan dengan kondisi pertanian di Indonesia yang cukup kompleks, dan membutuhkan perbaikan secara komprehensif.
https://money.kompas.com/read/2024/03/19/153913026/food-estate-dan-contract-farming-jauh-dari-kedaulatan-pangan