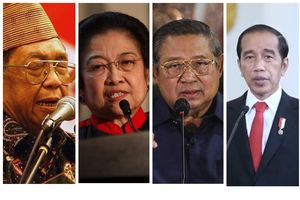Pragmatisme Lumbung Pangan

INDONESIA tengah bergulat dengan ironi defisit beras. Tingginya harga beras akibat defisit telah memukul banyak lapisan masyarakat.
Negeri agraris yang sempat mendapatkan penghargaan internasional atas keberhasilan swasembada beras pada 2022, nyatanya harus menelan pil pahit kelangkaan.
Di tengah gelombang polemik beras, publik kembali mempertanyakan esensi program lumbung pangan atau yang dikenal dengan istilah food estate.
Program yang digadang-gadang menjadi benteng ketahanan pangan nasional, nyatanya masih bergeming dalam menangani isu-isu instabilitas harga dan ketersediaan pangan.
Dengan dalih peningkatan jumlah penduduk yang terjadi bersamaan dengan turunnya luas baku lahan pertanian di Indonesia, pemerintah menarasikan food estate sebagai proyek genting. Pembukaan kawasan hutan untuk mega proyek ini terus dilakukan secara masif.
Kegagalan demi kegagalan food estate yang terjadi sejak pertama digulirkan pada era 1990-an nyatanya belum kunjung menjadi refleksi para pemangku kepentingan.
Sebaliknya pembangunan food estate kian menggeliat. Terbaru, Kementerian Koordinator Perekonomian merilis masterplan baru terkait perluasan food estate ke wilayah potensial seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Sumatera Selatan.
Masifnya perluasan food estate seolah jadi simbol keputusasaan bahwa sistem pertanian di negara kita nampaknya masih belum efisien dan berproduktivitas tinggi.
Lantas, apakah memang hanya food estate yang bisa kita upayakan untuk memperkuat ketahanan pangan bangsa?
Menelaah perspektif
Menilik ilmu agronomi, food estate dapat dikategorikan sebagai sistem pertanian ekstensif. Sistem ini menerapkan praktik pertanian pada skala yang sangat luas dengan proyeksi hasil produksi lebih berlimpah.
Meski pertanian ekstensif populer dikembangkan di banyak negara seperti Australia, Rusia, dan Amerika Serikat, berbagai hasil riset menunjukkan sistem pertanian ekstensif kurang cocok diterapkan di Indonesia.
Penggarapan pertanian ekstensif di Indonesia masih minim adopsi teknologi yang memadai. Selain itu, sistem ekstensifikasi yang hanya menanam satu komoditas atau juga disebut monokultur sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit, apalagi dengan lanskap Indonesia yang merupakan negara tropis.
Produksi dan produktivitas yang diharapkan kerap tidak sebanding dengan sumber daya lahan, air, dan input lainnya yang telah dikeluarkan. Alhasil, mubazir sumber daya menjadi suatu keniscayaan.
Sejalan dengan hal tersebut, merujuk pada data terbaru Bank Dunia, luasan hutan mengalami penyusutan sangat dramatis, yaitu dari luasan 100 juta hektare pada tahun 2000 menjadi hanya 50 juta hektare pada tahun 2020.
Beberapa riset menunjukkan hilangnya kawasan hutan karena akibat konversi hutan ke lahan pertanian.
Perihal legitimasi pembukaan kawasan hutan untuk food estate memang sudah diakomodasi pada Permen LHK Nomor 24 tahun 2020. Peraturan tersebut melegalkan kawasan hutan lindung untuk dialihfungsikan menjadi food estate.
Adapun prasyarat yang ditentukan, yaitu kawasan hutan lindung sudah tidak berfungsi sepenuhnya, serta sesuai untuk pengembangan food estate.
Menilik realisasi food estate per tahun 2023, setidaknya ada 760 hektare hutan beralih fungsi menjadi kebun singkong, sedangkan 16.000 hektare lainnya jadi cetak sawah.
Sayangnya hingga kini informasi akurat perihal luasan food estate tak pernah sampai ke publik. Data rinci komoditas apa yang ditanam, prognosa tingkat produktivitas, hingga seberapa besar panen dan cakupan distribusi hasil food estate terus membuat masyarakat bertanya-tanya.
 Kebun singkong seluas 600 hektare di Desa Tewai Baru, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, mangkrak
Kebun singkong seluas 600 hektare di Desa Tewai Baru, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, mangkrakPadahal para ahli telah memperingatkan singkong tidak cocok ditanam di Gunung Mas yang notabene memiliki karakteristik tanah berpasir.
Apatisme serupa teradopsi di pencanangan food estate baru di Papua yang menurut keterangan Kementerian Investasi akan ditanami tebu di atas lahan seluas satu juta hektare.
Jika menilik profil masyarakat Papua, mereka tentu lebih membutuhkan sagu daripada tebu.
Memang rencana ini digulirkan untuk mencapai swasembada gula nasional, namun penting diingat bahwa hutan tropis terbesar di Indonesia ada di Papua. Penanaman food estate yang tak terukur, hanya akan menghancurkan mega biodiversitas tanah Papua.
Kacamata holistik
Pembukaan food estate baru dengan konsep lawas yang cenderung destruktif hanya akan menciptakan ketimpangan ekonomi, konflik sosial hingga bencana.
Selain pangan, stabilitas lingkungan hidup serta pemerataan sosial dan ekonomi adalah hak asasi setiap manusia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah perlu menata ulang program food estate dengan menggunakan pendekatan holistik. Program mulia ini tak boleh hanya sekadar untuk ambisi memperkuat ketahanan pangan Indonesia, tetapi juga wajib mempertimbangkan berbagai aspek terutama lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Ilmu kehutanan sebetulnya sudah memberikan jawaban bagaimana hutan bisa berperan sebagai lumbung pangan, yakni melalui agroforestri atau wanatani.
Masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan sudah lama mempraktikkannya dengan menanam komoditas pertanian, peternakan dan perkebunan di antara dan bawah tegakan hutan.
Pembangunan food estate berbasis agroforestri artinya menempatkan keberadaan hutan sebagai aspek penting dalam produksi pangan yang turut memberi peran ekologis seperti perlindungan tanah dari erosi, penyimpanan karbon, dan penciptaan iklim mikro.
Dengan demikian, tak perlu lagi membabat hutan secara masif untuk dalih penyediaan pangan. Sebab ketahanan pangan mestinya dapat tercapai tanpa harus mengabaikan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.


























![[POPULER MONEY] Indonesia Selangkah Lebih Dekat Gabung Klub Negara Maju | Pesan Bea Cukai ke](https://asset.kompas.com/crops/8EX5-0wLzRHLhlwc2p_UVUtxxN0=/463x615:4163x3082/170x113/data/photo/2024/05/02/663355a709aa7.jpg)